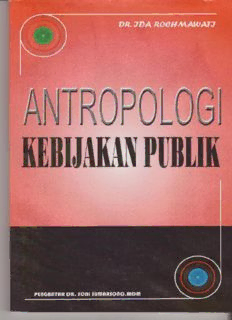Table Of ContentANTROPOLOGI
KEBIJAKAN PUBLIK
DR. IDA ROCHMAWATI
Perpustakaaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ANTROPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK
Cetakan: 1–Malang
Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. 2011
xi:221hlm: 16x24cm
ISBN:
ANTROPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK
Penulis:
DR. Ida Rochmawati
Tata Letak:
Deny Firmansjah
Grafis:
Heru Setiawan
Penyunting:
Drs. Ahmad Sofwani, M.Si
Hak Cipta pada penulis. Dilarang mengutip, memperbanyak,dan menerjemahkan
sebagian atau seluruhisibukuinitanpa ijin tertulis dari penulis.
Hak menerbitkan pada Yayasan Pembangunan Nasional Malang
Cetakan Pertama Maret 2011
Penerbit: Agritek YPN Malang, Jl. Soekarno-Hatta, Malang
Telp. 0341-495545, 0341-7585050, Faks: 0341-824644 Mobile: +628123575333
Isi buku di luar tanggung jawab percetakan
ii
PENGANTAR
SUATU kebijakan publik yang berhadapan dengan fakta berupa
keragaman etnis dan potensi konflik antar-etnis tidak bisa tidak
mempertimbangkan pendekatan antropologi dan perhitungan politik
ilmiah dalam perumusannya. Potensi konflik sedemikian masih
ditambah lagi dengan merasuknya wacana-wacana pasca reformasi
ke tubuh jasmani lokalitas yang masih lugu. Reformasi lantas
dijadikan sebagai “atas nama” bagi kepentingan “lokal" yang disunat
paksamenjadi hajat “perseorangan” dan “kelompok.”
Indonesia Pasca Reformasi: demokratisasi bergerak seperti arwah
yang berhembus dari atmosfer dunia ke lingkup nasional, menyusup
ke sendi-sendi komunitas-komunitas lokal, untuk kemudian
ditafsirkan menurut kepentingan politik, ekonomi, sosial yang boleh
jadi masih membawa-bawa sentimen primordial. Motif-motif
oportunistis, materialistis dari para politisi yang ingin
“mewirausahakan negara” membuat panggung sebesar taplak meja
di bola dunia itu riuh rendah, panas dan bergolak. Itulah yang coba
dipetakan DR. Ida Rochmawati dalam buku ini.
Para peneliti ada yang menggunakan periodisasi untuk membedakan
corak perubahan pada tiap-tiap babakan menurut sifat-sifat tipikalnya
yang paling kentara. Namun sejatinya cultural lag, itulah yang
memicu konflik dan masalah-masalah. Orang lalu menyalahkan Orde
Baru karena dianggap memaksakan nasionalisme-simbolis yang
mengubur kesempatan etnik-etnik lokal berkiprah di tataran lokalnya
sendiri. Ketika simbol itu runtuh, maka sentimen-sentimen primordial
yang lama terpendam pun berlompatan dengan liarnya, mencari-cari
asal jati dirinya, mencakar-cakar sesamanya, sambil mencocok-
cocokkan baju dengan payung reformasi yang baru.
iii
Pemekaran daerah adalah keniscayaan politik dalam era otonomi.
Kelas menengah, teknokrat dan kaum akademisi sibuk merumus
langkah-langkah saintifik bagi perumusan kenegaraan yang baru
pasca keruntuhan Suharto itu. Sempat ada yang mengusulkan
federalisme, adapula yang mengusulkan desentralisasi bertahap.
Bagi Kalimantan Barat pasca-reformasi, politik etnis identik dengan
politik elit. Orang Dayak merupakan kelompok sosial yang paling
sering terlibat dalam pergumulan politik lokal dengan menggunakan
sentimen etnis. Mayoritas mereka menghendaki representasi
birokrasi lebih besar akibat sejarah panjang marjinalisasi. Partai
politik yang berwarna nasional, demokrat, atau keagamaan tidak
cukup menampung hasrat pasca-keterpinggiran itu hingga
organisasi-organisasi kemasyarakatan bercorak adat dengan
pengaruh politik yang kuat pun dijadikan sebagai kendara, misalnya
Majelis Adat Dayak. Dengan pencitraan selaku suku terbelakang
namun terdeprivasi, seperti juga Betawi di DKI Jakarta atau suku-
suku lokal di Papua, pada akhirnya orang dayak berhasil menduduki
posisi-posisi penting politik di daerahnya, dan usai menggumuli
konflik bersama etnik lain (Melayu, Madura, Jawa, dan lain-lain)
mereka pun belajar berbagi kekuasaan untuk mengakhiri kompetisi
politik dan konflik etnik yang penuh dengan kekerasan, secara damai.
Aktor dan Faktor
Dr. Ida merumuskan pendekatannya melalui dua elemen penting:
aktor dan faktor. Pada aktor dapatlah ditelaah motif-motif individu dan
kelompok besertareview historis serta rekam jejak dan kemungkinan-
kemungkinan sepak terjang mereka di masa depan. Pada faktor
dapatlah ditelusuri unsur-unsur kultural dan struktural mulai dari lapis
luarnya yang artifisial sampai ke kerak kejiwaannya yang paling
substansial.
Jika ada isu desentralisasi dan pemekaran wilayah, maka lapis
artifisial itu adalah administrasi formal penyelenggaraan politik,
sedangkan kerak substansialnya adalah desentralisasi peran politik
dan fiskal. Kalau ada aktor yang naik panggung, apakah secara
iv
substansi mereka sudah merepresentasikan kepentingan kelompok
sosial yang lebih luas di bawahnya? Apakah desentralisasi benar-
benar membawa berkah bagi warga tempatan? Atau hanya
memberkahi para aktor yang senang berjudi politik dan hidup untung-
untungan dari “mewirausahakan negara”?
Maka, wajar kiranya, ketika panggung politik itu hanya bisa didaki
lewat partai politik dan lembaga DPRD yang notabene masih
diembel-embeli semangat berjudi tadi, maka lembaga-lembaga
swadaya masyarakat dan majelis adat lebih dilirik pemangku birokrasi
di level pusat dan propinsi. Besar harapan, bahwa LSM dan lembaga-
lembaga adat tersebut akan mewakili kepentingan warga awam untuk
menikmati berkah otonomi yang lebih hakiki pasca reformasi.
Demikian pula, besar harapan agar mereka tidak terseret pada
oportunisme ala parpol, dan tarikan-tarikan ego sektoral kedaerahan
yang masih harus menjadi agenda keprihatinan pada tahun-tahun
belakangan.
Kebijakan publik berlandas antropologi itulah yang moga-moga
merupakan langkah bijak yang mewadahi kepentingan publik
sebenarnya.
Jakarta, Maret 2011
Dr. Soni Sumarsono, MDM
v
PENGANTAR PENULIS
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan kajian
buku yang berjudul ANTROPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK.
Buku mengkaji masalah desentralisasi dan demokrasi yang
ada di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Barat pada
khususnya. Motif utama yang melatarbelakangi kebijakan pemekaran
daerah ini pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencapai dua hal
penting yang menjadi ciri administrasi publik modern yaitu
pemerataan ekonomi dan keadilan politik. Secara teoritis,
pemerataan ekonomi dan keadilan politik akan tercapai jika terjadi
desentralisasi sehingga pemerintah menjadi lebih dekat dengan
masyarakatnya. Dan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang
baik, Merilee S Grindle (2007) dalam Going Local; Decentralization,
Democratization and the Promise of Good Governance mengingatkan
perlunya pemerintah merespon sejumlah perbedaan yang ada dalam
suatu negara menjadi peluang baru yang lebih menjanjikan bagi
persaingan politik, enterpreneurship sektor publik, modernisasi
administratif, dan aktivitas masyarakat sipil (civil society).
Untuk dapat mengungkap apakah pemekaran daerah di
Kabupaten Pontianak memenuhi syarat keberakaran lokal
sebagaimana going local dari Grindle, maka penulis memanfaatkan
beberapa teori pendukung, antara lain konsep desentralisasi sebagai
konsolidasi demokrasi dari Adam Przeworski. Dalam Democracy,
Accountability and Representation (1999) Przeworski mendalilkan
bahwa demokratisasi yang ideal di masa transisi merupakan sebuah
pelembagaan atau mekanisme institusionalisasi dari konflik yang
berkelanjutan dan pelembagaan demokrasi yang mencakup cita-cita
partisipasi dari seluruh kelompok yang berbeda cita-cita, kepentingan
dan ideologi. Desentralisasi dengan demikian merupakan konsolidasi
demokrasi. Penulis juga memanfaatkan teori pendukung lain seperti
dari BC Smith dalam Decentralization the Territorial Dimension of the
vi
State (1985) yang pada intinya menekankan bahwa desentralisasi
merupakan pilihan politik dan demi tujuan politik. Asumsi Smith
didasarkan atas adanya perbedaan normatif antara negara, provinsi,
tipe rezim dan ideologi. Pilihan substansi dari lembaga-lembaga yang
telah terdesentralisasi adalah menyangkut semua hal, salah satunya
adalah politik. Tujuan negara dalam membentuk atau mendesain
ulang konstitusi adalah federasi atau reorganisasi sebuah sistem dari
regional atau pemerintah daerah demi tujuan politik. Selain itu, teori
pendukung dari Ortwin Renn (1992) dalam teori Metafora Arena juga
menjadi referensi penting bagi penulis, karena Renn mengedepankan
dua asumsi dasar dalam memaknai peran aktor dalam kebijakan
publik, yaitu: a) Model ini tidak memandang proses kebijakan publik
sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan sebagai
serentetan upaya negosiasi berlapis-lapis yang melibatkan kelompok-
kelompok aktor yang langsung berpatisipasi, b) Dalam melihat peran
aktor pada proses kebijakan itu, teori metafora arena sosial sangat
selektif. Kongkretnya, model ini hanyalah berkepentingan pada
perilaku individu atau kelompok-kelompok sosial yang secara sengaja
diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk melihat
bagaimana beroperasinya konsep metafora arena dari Renn yang
melibatkan para aktor dalam sebuah kebijakan publik, penulis juga
memanfaatkan konsep dialog otentik dari Hajer dan Wagenaar
sebagai teori pendukung berikutnya. Hajer dan Wagenaar (2003)
pada intinya mengadaikan bahwa deliberasi dalam kebijakan terletak
pada dialog otentik yang melibatkan kekuatan jaringan dalam
masyarakat. Hajer dan Wageenar mencontohkan bahwa konflik
dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dan faktor etnis dan
perbedaan budaya sebagai bentuk nyata dari adanya jaringan dalam
masyarakat, sehingga diperlukan adanya dialog otentik atau dialog
kolaboratif dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Sebagai
rekomendasi teoritik dari elaborasi konsep-konsep di atas, penulis
memanfaatkan teori demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas.
Dalam Communication and the Education of Society (1979)
Habermas mengandaikan bahwa demokrasi pada dasarnya tidak
dibangun atas dasar suara mayoritas (seperti model demokrasi
republikan) atau kebebasan individu (seperti model demokrasi
vii
liberal), tetapi lebih merupakan aksi para partisipan melalui tindakan
saling pengertian, berargumentasi, dan perjanjian dalam struktur
pembentukan opini dan kehendak. Tujuan demokrasi deliberatif
adalah memperoleh legitimasi yang didasarkan pada rasionalitas
yang mumpuni dalam proses memutuskan sebuah kebijakan. Sebuah
institusi dibentuk guna mengakui pelbagai kepentingan kelompok
yang terbangun dalam proses deliberasi kolektif yang mencakup
rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan individu. Dengan demikian
maka hasil yang dicapai adalah rasionalitas dan legitimasi. Dalam
proses deliberasi kebijakan publik tidak semata-mata mengutamakan
prosedur dan suara mayoritas warga negara, akan tetapi negara
harus lebih dulu mengajak dialog atau musyawarah masyarakat sipil
untuk mencapai konsensus atau kesepakatan dalam suasana yang
diskursif, dengan demikian maka proses deliberasi kebijakan
pemekaran daerah akan berjalan secara fair dan legitimet. Melalui
gambaran umum tentang teori utama dan teori pendukung yang
diacu dalam studi ini, maka diharapkan akan diperoleh gambaran
yang utuh tentang bagaimana bekerjanya teori Going Local, teori
Konsolidasi Demokrasi, teori Metafora Arena, teori Dialog Otentik
yang melibatkan jaringan aktor dalam masyarakat, dan teori
Demokrasi Deliberatif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam menganalisis proses-proses ekonomi politik kebijakan
pemekaran daerah sebagaimana tema utama dalam kajian ini.
Sebagai sebuah studi evaluatif, kajian ini menggunakan
kerangka studi evaluasi kebijakan post facto. Studi evaluasi demikian
dalam pandangan para proponen evaluasi kebijakan diperlukan untuk
menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan.
Kajian ini pada dasarnya juga merupakan kajian yang mengakaji
realita dunia (noumena) seperti tema utama dalam studi ini yaitu
tentang pemekaran daerah di tengah dinamika konflik etnis di
Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai sebuah realitas
pemekaran daerah tidak dapat dilepaskan dari tarik menarik
kepentingan di antara para aktor yang terlibat.
Analisa terhadap data yang dihasilkan dilapangan dengan
menggunakan teori yang digunakan dalam kajian ini, seperti yang
viii
diungkapkan oleh Grindle dengan Going Localnya, Adam
Pzresworsky yang secara nyata memberikan tesisnyan tentang
pemahaman konsulidasai demokrasi serta Otwin Renn melalui
metafora arena dalam memotret motif aktor dalam sebuah kebijakan.
Bagian Penutup berisikan simpulan, saran dan rekomendasi,
dimana pada bab terakhir ini: pertama, kebijakan pemekaran daerah
yang hanya bersifat administratif berupa pelimpahan kewenangan
administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
cenderung menguntungkan pemerintah pusat dan lemah
legitimasinya di hadapan rakyat, karena tidak diimbangi dengan
desentralisasi politik dan desentralisasi fiskal. Kedua, kebijakan
pemekaran daerah secara administratif tanpa diimbangi
desentralisasi politik dan fiskal hanya menempatkan pemerintah
daerah sebagai objek dari pemerintah pusat, karena pemerintah
daerah hanya sebagai “residual element” pada tahap awal
pembangunan di bawah kontrol kapatalisme. Ketiga, kebijakan
pemekaran daerah secara adminsitratif hanya akan memindahkan
wilayah konflik lama ke daerah baru (DOB hasil pemekaran)
sebagaimana proses transisi demokrasi yang bersifat semu karena
tidak diimbangi dengan proses konsolidasi demokrasi secara
memadai, sehingga diperlukan model demokrasi deliberatif dalam
bentuk kebijakan Desentralisasi yang berbeda untuk Indonesia
dengan tujuan memperoleh legitimasi berdasarkan rasionalitas yang
mumpunidalam proses memutuskan sebuah kebijakan.
Penulis mengharapkan saran yang membangun agar kajian
buku ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Malang, Februari 2011
Penulis
Ida Rochmawati
ix
Description:tiga tipe institusi politik, yaitu aparat administrasi negara (birokrasi); institusi representasi Management Development December 1993, Reprinted.